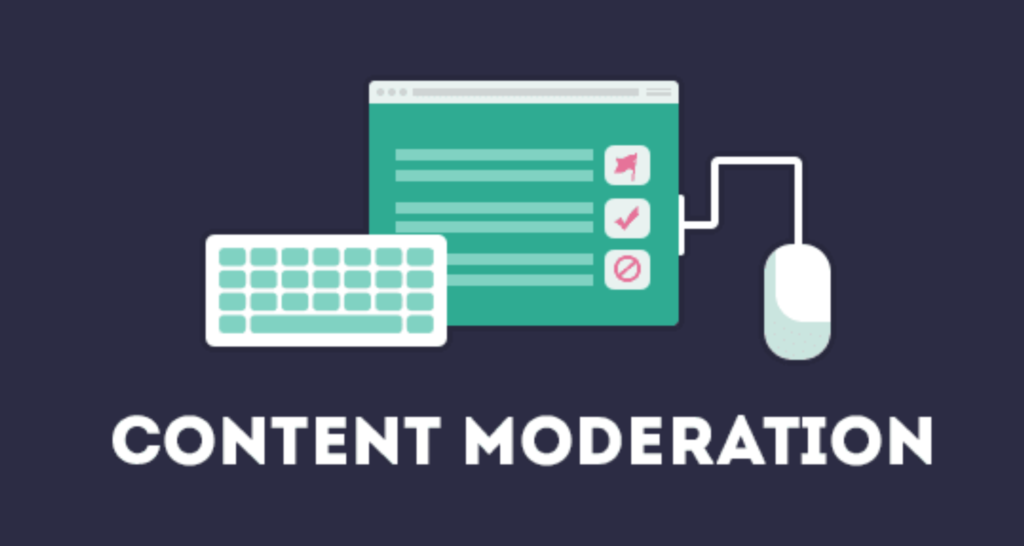Pada 14 Januari 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas gugatan terhadap pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran yang diajukan RCTI dan iNews. Isi amar putusan yang dibacakan hakim ketua Anwar Usman menyebutkan MK “menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya”. Dalil-dalil yang diajukan para pemohon dinilai tidak berdasar.
Dalam gugatannya (27/05/2020) RCTI dan iNews menilai Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran bersifat ambigu karena tidak mengkategorikan Over-The-Top sebagai bentuk penyiaran. Argumentasinya, konten/video on demand/streaming tidak berbeda dengan televisi karena memproduksi luaran yang sama, yakni konten audio-visual. Tidak berhenti hanya dengan menggugat UU Penyiaran, dalam pelbagai berita di media disebutkan RCTI dan iNews telah mengusulkan untuk mengganti definisi penyiaran pada pasal 1 ayat 2 hingga mencakup layanan Over-The-Top/OTT (khususnya konten/video on demand/streaming).
Jika usul ini diadopsi, implikasinya sebagaimana dinyatakan oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Ahmad M Ramli “akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial akan diharuskan jadi lembaga penyiaran yang wajib berizin.”
Menaruh OTT dalam konteks penyiaran adalah sebentuk kegagalan memahami perbedaan mendasar antara teknologi analog dan digital serta implikasi sosial dan hukum yang menyertainya. Jamak diketahui, penyiaran menggunakan teknologi analog. Pemancarluasan siaran menghasilkan model komunikasi yang serempak atau kita kenal dengan istilah komunikasi massa. Kita yang menyaksikan MNC di Jakarta dengan saudara kita di Papua akan mendapati tayangan yang sama. Implikasi sosialnya, media penyiaran tidak memberi agensi yang luas pada publik. Inilah antara lain mengapa di banyak negara demokratis, selain karena ia menggunakan ranah publik (gelombang elektromagnetik), media penyiaran diregulasi secara ketat. Tujuannya untuk memastikan bahwa publik “yang tidak punya banyak pilihan” terlindungi dari dampak konten negatif.
Sementara model-model komunikasi dari media digital menggunakan sistem jaringan. Dua orang dari dua lokasi yang berbeda kala membuka Youtube akan mendapati sajian tayangan yang berbeda. Aspek lainnya adalah, media digital seperti Youtube juga memungkinkan user-generated content/UGC. Artinya, pelaku komunikasinya tidak lah satu pihak. Logika produsen-konsumen dalam penyiaran tidak berlaku dalam logika digital. Dalam konteks digital semua orang adalah prosumen (produsen sekaligus konsumen). Implikasi sosialnya, di media digital, publik punya agensi yang lebih luas. Itulah mengapa aspek pengaturan media digital atau OTT umumnya jauh lebih longgar. Kebanyakan pengaturan terkait OTT menyasar pada aspek bisnis ketimbang konten. Adapun regulasi konten terbatas pada hal-hal yang dianggap amat berbahaya seperti ujaran kebencian atau pornografi anak. Di luar itu, publik diharapkan memiliki kedewasaan untuk memilih konten yang dikonsumsi atau diproduksinya sendiri.
Kesadaran untuk membedakan implikasi sosial dan hukum dari aplikasi teknologi digital dan analog ini penting, agar kita tidak sembarangan menyamaratakan keduanya. Pasalnya, menaruh OTT dalam definisi penyiaran dapat berdampak membunuh potensi dari OTT sebagai alat demokrasi maupun ekonomi.
Berkaca dari pengalaman sejumlah negara
Dalam merespon disrupsi yang diakibatkan oleh perkembangan OTT, negara-negara menggunakan dua jenis pendekatan regulasi yang berbeda terhadap OTT: menggunakan Paradigma Lama seperti di Thailand atau menggunakan Paradigma Baru seperti di Australia.
Regulator penyiaran dan telekomunikasi di Thailand, National Broadcasting dan Telecomm Commission (NBTC) meregulasi penyelenggara OTT agar mendaftarkan diri (mendapat lisensi) dan tunduk pada regulasi NBTC (Film and Video Act B.E. 2551), yang mengharuskan setiap produk film dan video melalui proses sensor.
Alih-alih membuat kerangka regulasi yang lebih sesuai dengan karakter teknologi dan fungsi sosial OTT, NBTC memilih menyetarakan OTT dengan penyiaran. Dengan cara ini, seolah kesetaraan atau keadilan usaha telah dicapai. Padahal ia menyisakan banyak masalah yang antara lain bisa diidentifikasi dari dua pertanyaan. Pertama, mungkinkah secara teknologis pengawasan atau sensor atas OTT dilakukan secara menyeluruh (tidak hanya OTT yang memiliki pasar yang besar)? Dan jika pun bisa, bagaimana memastikan pengawasan dalam bentuk sensor dan sanksi tanpa harus mengorbankan hak asasi manusia untuk berekspresi? Kita tahu, jawabannya hampir mustahil.
Tapi tentu, sebagian negara lain menempuh proses yang berbeda. Australia adalah salah satu yang menggunakan paradigma baru dalam mengatur layanan OTT. Paradigma baru ini dicirikan oleh sikap regulator yang antisipatif dan penerapan kebijakan yang berangkat dari pemahaman memadai atas perbedaan konteks sosial teknologi antara OTT dan penyiaran.
Dalam sistem hukum Australia, konten internet diatur oleh Australian Communications and Media Authority (ACMA). Lembaga ini mengeluarkan peraturan berdasarkan keputusan klasifikasi layanan OTT video dari Classification Act (1995) yang mengatakan bahwa layanan OTT dengan sistem berlangganan tidak dapat menggunakan pendekatan pengaturan yang sama untuk klasifikasi seperti penyiaran. Oleh karena itu, layanan OTT video sejenis tidak tunduk pada peraturan untuk TV free-to-air, kabel atau satelit. OTT diatur menggunakan self-regulatory model, artinya penyelenggara OTT diharuskan mengatur dirinya sendiri.
Kendati demikian, bukan berarti pemerintah dan warga negara Australia kehilangan kedaulatan dihadapan OTT. Sebagai wakil dari publik Australia, ACMA berperan memberikan panduan prinsip-prinsip dasar dari self-regulatory yang nantinya akan diterapkan oleh OTT dan menerima complain dari warga negara bilamana ada konten OTT yang dinilai merugikan mereka.
Mengingat sifatnya yang melintas batas-batas administratif negara, idealnya kerangka regulasi untuk mengatur OTT dibuat oleh International Telecommunications Union (ITU), badan khusus PBB yang bergerak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Namun, kerja multilateral global tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Karenanya, sambil menunggu ITU bekerja, belajar dari pengalaman negara-negara lain adalah hal paling masuk akal saat ini.
Pertanyaan kemudian, pada negara mana kita akan belajar, Thailand atau Australia? []
Damar Juniarto adalah Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network dan Muhamad Heychael adalah Penulis, pengajar, dan peneliti media.
Opini telah diterbitkan kompas.com pada 15 Januari 2021 https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/16391421/mengatur-penyiaran-digital-pascaputusan-mk-terkait-gugatan-rcti-dan-inews?page=all#page2